Kota
Banda Aceh
Judul
Siasat Untuk Maslahat Legalitas Komunitas di Aceh
Penulis
Akbar Rafsanjani

Di Aceh, komunitas film lahir dan tumbuh sebagai siasat dari keterbatasan yang dihadapi di ekosistem perfilman lokal, terutama di lini produksi. Mulai dari sumber dana, sumber daya manusia yang terampil, hingga kepemilikan peralatan produksi film. Anggota komunitas film tersebut awalnya adalah individu yang punya relasi (pertemanan). Kemudian mengajak yang lainnya, teman dari teman yang punya keahlian mengoperasi kamera, atau jago editing. Komunitas film muncul untuk berbagi resources yang dimiliki setiap individu;
Namun, keberlanjutan sumber dana produksi film dari individu dalam komunitas film di Aceh ternyata tidak bisa menyokong keberlangsungan aktivitas mereka dalam skala besar. Ini kemudian membawa komunitas film di Aceh untuk melihat kemungkinan sumber dana produksi film yang mungkin untuk diakses. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pemerintah kota/kabupaten lewat kedinasan dan pemerintah pusat melalui kementerian. Sumber pendanaan lain adalah perusahaan swasta, tetapi ini sangat kecil karena mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh.
Pendanaan produksi film dari pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah pusat kemudian membentuk model komunitas film di Aceh yang seragam dalam hal pengurusan legalitas. Komunitas film yang tidak lagi hanya sebagai tempat berbagi resources individu-individu, tetapi komunitas film yang punya legalitas untuk bisa melewati birokrasi dalam memperoleh sumber dana dari pemerintah.
NGO, Film Advokasi, Hingga Lahirnya “Komunitas Film” di Aceh
Tahun 2013 menandai tumbuhnya ekosistem perfilman di Aceh. Hal itu terlihat dari hadirnya komunitas Aceh Documentary. Aceh Documentary diinisiasi pertama kali untuk merespon kebutuhan sumber daya manusia dalam produksi film. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya sekolah film di Aceh. Selain itu faktor konflik bersenjata yang berlangsung lama juga mengakibatkan pendidikan dan kegiatan kreatif tidak bisa berjalan dengan stabil. Akibatnya kegiatan kesenian dan kebudayaan dan sumber daya manusianya tidak berkembang.
Pada tahun 2012, Azhari dan kawan-kawan memproduksi film yang berjudul +1Menit Di Belakang 0 KM (2012). Film ini ingin menggambarkan pendidikan di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar yang tidak memiliki cukup tenaga pengajar. Azhari dan kawan-kawan saat itu memutar film tersebut di warung-warung kopi di Banda Aceh disertai dengan diskusi setelah menonton serta mengumpulkan buku untuk dikirim ke anak-anak di Pulo Aceh.
Penggunaan media film untuk advokasi isu-isu sosial, lingkungan, dan lainlain sudah dimulai sejak hadirnya Non Governmental Organization (NGO) untuk resolusi, rekonsiliasi dan Hak Asasi Manusia pada masa konflik Pemerintah Indonesia-GAM dalam periode tahun 2000-an. Produksi film oleh NGO (seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat - ELSAM) ini melibatkan wartawan, aktivis, maupun warga lokal Aceh. Film Village Goat That Takes the Beating (2001), Abracadabra (2003) karya Aryo Danusiri adalah satu dari beberapa contoh film dokumenter yang merekam isu sosial semasa konflik Pemerintah Indonesia-GAM.
Selama konflik bersenjata (1998) hingga peristiwa Tsunami (2005) merupakan periode dimana berbagai NGO hadir di Aceh untuk kepentingan resolusi konflik maupun agenda kemanusiaan. Periode hadirnya NGO ini turut melahirkan pembuat-pembuat film yang mengisi satu titik dalam linimasa sejarah perfilman di Aceh, dimana mereka yang pernah bekerja untuk produksi film bersama NGO tersebut mewarisi kemampuan pembuatan film. Sebelumnya sebagian dari mereka adalah wartawan lepas, sebagian lain adalah seniman panggung, aktivis, hingga warga biasa. Generasi pembuat film ini yang kemudian memanfaatkan keterampilannya untuk memproduksi film-film komedi yang kemudian dijual dalam bentuk VCD di seluruh Aceh melalui toko-toko kaset DVD/VCD maupun lapak yang digelar di pasar-pasar di Aceh dengan harga Rp 15.000,- hingga 25.000,-. Salah satu yang paling terkenal dan berhasil diproduksi sampai 14 volume adalah film Eumpang Breuh yang diproduksi berkala dari tahun 2006 hingga 2018.
Dua tujuan produksi film ini, advokasi dan komersial, terus mengisi cerita perfilman di Aceh sampai sekarang. Film advokasi yang dimaksud adalah yang diproduksi dengan tujuan menyuarakan pendapat terkait isu sosial, lingkungan, dan sebagainya. Dimana distribusi maupun eksibisinya juga tidak untuk meraup keuntungan. Film ini biasanya dibuat dalam genre dokumenter. Berbeda dengan film komersial yang dimaksud diatas, adalah film yang diproduksi untuk kepentingan meraup keuntungan dengan berbagai metode distribusi dan ekshibisi. Film ini lebih banyak diproduksi dalam genre fiksi dan biasanya berbentuk komedi.
Setelah perubahan medium dari VCD ke digital, generasi pembuat film komersial yang mewarisi kemampuan membuat film pada NGO tadi sempat vakum karena tidak bisa memanfaatkan secara maksimal platform digital baru (seperti Youtube dan lain-lain) dalam hal distribusi dan eksibisi. Pada saat inilah generasi sineas dokumenter advokasi terlihat dominan dalam perfilman di Aceh.
Setelah film +1 Menit Di Belakang 0 KM berhasil memberi perubahan terhadap pendidikan di Pulo Aceh, Aceh Besar, Azhari dan kawan-kawan mulai melihat bahwa media film tidak hanya sekadar hiburan belaka. Film bisa menjadi corong untuk menyampaikan aspirasi masyarakat maupun kritik terhadap kebijakan publik. Ia tidak memandang kritik adalah bagian dari perlawanan terhadap pemerintah. “Kita tidak mengkritik pemerintah. Kita hanya memperlihatkan realita yang ada di lapangan agar mereka tahu yang sebenarnya. Kita hadirkan mereka untuk menonton film, kemudian sama-sama berdiskusi untuk mengambil jalan terbaik bagi penyelesaian masalah tersebut” sebut Azhari.
Kemudian, mereka yang terlibat dalam aksi tiga minggu untuk Pulo Aceh ini; Azhari, Shinta Devi, Fauzi, Faisal dan Jamaluddin Phonna yang saat itu sedang melanjutkan pendidikan di Malang, mewacanakan sebuah kegiatan kompetisi film. Azhari dan Shinta melakukan silaturahmi dengan berbagai unsur seniman secara pribadi untuk meminta masukan terkait keinginan mereka mengadakan sebuah kegiatan kompetisi film di Aceh.
Para seniman tersebut hadir dan berkumpul pada malam di launchingnya Aceh Documentary pada tanggal 27 Februari 2013. Di Sisi yang lain, Faisal Ilyas membangun komunikasi serta mengajak teman-teman filmmaker di Aceh; RA Karamullah, Amri,Fahri, Helmi, Eka Wandri, dan lain-lain untuk ikut bergabung. Faisal yang sebelumnya juga melanjutkan pendidikan sarjananya di Malang meminta Jamaluddin Phonna yang sedang berada di Malang untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman-teman di Malang, salah satunya adalah Taufan Agustyan. Taufan kemudian berangkat ke Aceh untuk membantu terlaksananya program Aceh Documentary Competition pertama tahun 2013. Aceh Documentary Competition mengikuti pola yang dilakukan Eagle Documentary Competition. Peserta yang lolos seleksi dibekali pengetahuan terkait keseluruhan proses produksi film dokumenter. Proses ini kemudian menghasilkan film dokumenter pendek dari ide cerita yang diajukan para peserta.
Program Aceh Documentary Competition pertama dibiayai secara mandiri oleh Azhari dan kawan-kawan, yang sebelumnya sudah aktif memproduksi karya audio visual. Dari Aceh Documentary Competition tahun pertama, lahir sepuluh orang sutradara yang kemudian disebut sebagai alumni ADC. Lima orang dari mereka sekarang masih menekuni profesi sebagai pegiat perfilman di Aceh dan satu orang di Jakarta. Ini memberi semangat kepada Aceh Documentary, bahwa langkah yang mereka rencanakan memberi dampak positif dan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal.
Namun penyelenggaraan workshop ini membutuhkan biaya besar karena harus mendatangkan peserta dari luar kota Banda Aceh. Untuk kelangsungan program, Faisal Ilyas, direktur Aceh Documentary dan juga bagian pendiri Aceh Documentary Competition, mengusulkan Aceh Documentary membentuk badan hukum berupa yayasan. Faisal berpendapat bahwa untuk keberlanjutan, Aceh Documentary Competition bisa menargetkan pendanaan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Dalam jangka panjang, jika Aceh Documentary Competition dibentuk dengan legalitas berupa yayasan, akan dapat dijadikan sebagai sekolah film.
Komunitas Menuju Legalitas

Aceh Documentary 2014 Training. Sumber_ Aceh Documentary
Pada tahun 2014, Aceh Documentary resmi menjadi Yayasan Aceh Dokumenter (YAD). Tahun kedua, program Aceh Documentary berhasil mendapat sokongan dana dari The Asia Foundation, yang dimanfaatkan untuk mengadakan program produksi film dokumenter bagi alumni Aceh Documentary Competition tahun sebelumnya. Dalam setahun, YAD bisa memproduksi lima hingga sepuluh film dokumenter dan menghasilkan sepuluh sampai dua puluh orang lulusan.
YAD harus bermanuver untuk memperoleh pendanaan. Dukungan dana dari lembaga donor seperti The Asia Foundation tidak bisa didapatkan setiap tahun. Hal tersebut disadari betul oleh Faisal. Oleh karena itu, mereka harus menabung dana yang diperoleh pada tahun 2014 untuk bisa menghidupi program hingga dua tahun kedepan. Orang-orang yang bekerja dalam YAD belum digaji. Semuanya bekerja secara sukarela. Pendapatan hidup mereka bersumber dari pekerjaan yang dikerjakan secara personal, seperti memproduksi video profil lembaga, perusahaan, dan dokumentasi pernikahan.
Setelah menjadi yayasan, Aceh Documentary masih menjalankan kegiatannya layaknya seperti sebuah komunitas. Menurut Faisal, legalitas hanya prasyarat untuk bisa menerima pendanaan dari pemerintah maupun lembaga donor. Sebagai organisasi formal, tiap anggota menjalankan fungsi dan peran sesuai latar belakang. Misalnya, Faisal yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang manajemen dan bisnis, bertugas untuk membuat roadmap Aceh Documentary serta mencari sumber dana, serta mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif, misalnya laporan keuangan.
Anggota lain bertanggung jawab untuk menjalankan program Aceh Documentary Competition, yang terbagi ke dua cabang yaitu pendidikan seperti pengajaran penulisan naskah dan penyutradaraan, dan produksi yang berupa pengajaran terhadap penggunaan kamera hingga penyuntingan gambar.
Keberlanjutan Komunitas FIlm Dengan Kolaborasi
Di tahun yang sama, RA Karamullah mendirikan komunitas film di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Setiap tahun komunitas yang dinamai Trieng ini rutin merekrut mahasiswa baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Namun, komunitas Trieng, sekalipun mendapat dukungan moril dari beberapa dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tetapi tidak mendapatkan dana rutin dari kampus. Menurut Refanda, yang menjadi ketua Komunitas Trieng dari tahun 2019 sampai dengan 2021, “Komunitas Trieng baru diresmikan sebagai UKM kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada bulan September 2022”.
Untuk produksi film, Komunitas Trieng biasanya bermodal dari hasil urunan. Trieng bisa memproduksi dua hingga tiga film dalam setahun dan mengadakan ekshibisi mandiri dengan memanfaatkan ruang sekretariat di kampus. Fasilitas ruangan itu adalah satu-satunya sokongan kampus. Salah satu program rutin tahunan adalah ekshibisi bertajuk "December to Remember", yang menayangkan film-film produksi Trieng dalam setahun. Sejak didirikan pada 2014, Komunitas Trieng tetap bertahan dan telah memproduksi puluhan film pendek.
Di luar eksibisi mandiri, Komunitas Trieng juga mengadakan kolaborasi dengan komunitas film lain di Banda Aceh. Salah satunya dengan Komunitas eksibisi Aceh Menonton. Saat pertama kali dicetuskan, Aceh Menonton diinisiasi oleh alumni Aceh Documentary; Muhammad Fauzi, Muhammad Hendri, dan Irza Ulya. Aceh Menonton fokus pada pemutaran film-film yang diproduksi oleh komunitas film di Aceh.

Produksi Film Aceh Documentary 2014. Sumber_ Aceh DocumentaryBW
Aceh Menonton melakukan pemutaran film dua kali dalam sebulan. Karena durasi pemutaran yang lumayan banyak itu, jumlah film Aceh tidak cukup sehingga Aceh Menonton harus memutar film-film dari luar Aceh. Program pemutaran Aceh Menonton dirancang secara tematik dan biasanya mengikuti isu yang aktual. Misalnya, isu pendirian perusahaan tambang, hari kesaktian Pancasila, hari penyerangan pertama Belanda ke Aceh, dan sebagainya.
Sejak pertama kali diadakan, Aceh Menonton dibiayai secara mandiri. Aceh Menonton kerap memanfaatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, cafe, universitas, dan komunitas lain untuk memperoleh tempat pemutaran. Misalnya, Aceh Menonton bekerjasama dengan Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh-Sumut (BPNB Aceh-Sumut) untuk penggunaan Mini Teater BPNB sebagai ruang putar. Di lain kesempatan, Aceh Menonton mengadakan pemutaran di kafe. Pemutaran itu merupakan hasil kerjasama Aceh Menonton dengan Ivory Cafe, Banda Aceh yang difasilitasi oleh Ruko 19 (Rumah Komunitas 19), sebuah program kolaborasi yang diinisiasi oleh PT. Sampoerna Tbk bersama Ivory Cafe dan radio Kontiki FM. Di luar tempat, Aceh Menonton berkolaborasi dengan komunitas lain untuk mendapatkan film.
Pemutaran Aceh Menonton bersifat gratis dan belum pernah mengambil bayaran dari tiket. Film-film yang diputar pun diperoleh secara gratis dari baik langsung dari pembuat film atau pegiat komunitas film di jejaring mereka. Aceh Menonton beberapa kali bekerjasama dengan lembaga-lembaga advokasi seperti KontraS dan LBH Banda Aceh.
Saat ini, Aceh Menonton sudah mempunyai legalitas di bawah CV. Reprolog Production yang didirikan oleh Muhammad Hendri dan Irza Ulya. Menurut Irza, Reprolog Production ada untuk menghidupi program Aceh Menonton. Dengan adanya rumah produksi ini, pengelola Aceh Menonton bisa mendapatkan penghasilan dari produksi film maupun video pesanan.

Syuting Film Hana Gata oleh Fisuar. Sumber_ FisuarBW
Komunitas film di Aceh terhubung lewat kerjasama-kerjasama produksi maupun ekshibisi. Menurut Azhari komunitas film di Aceh juga terbentuk karena saling membutuhkan,"ada kendala pada kepemilikan alat, seperti kamera, kemudian mereka berkumpul untuk saling melengkapi". Hubungan itu terus terjadi ketika satu komunitas film membutuhkan yang lain, misalnya kerjasama antara komunitas film yang fokus pada produksi dengan komunitas ekshibisi.
Komunitas Fisuar adalah salah satu contoh komunitas film yang terhubung dengan yang komunitas lainnya saat mereka memerlukan cara untuk eksibisi film mereka. Fisuar lahir secara organik, bukan karena pernah mengikuti lokakarya Aceh Documentary maupun tergabung dalam komunitas film kampus. Fisuar terbentuk berangkat dari minat Faris Mukammil dan Arif Missuari pada film. Mereka adalah dua mahasiswa yang bertemu awalnya di warnet sebagai gamer. Setelah perkembangan jaringan internet yang menyebabkan warnet tutup, mereka mulai tertarik untuk menjadi konten kreator dengan memproduksi film pertama yang berjudul Bajeung (2019).
Bajeung (2019) dipilih oleh Aceh Menonton untuk diputar pada acara peringatan Hari Film Nasional, 30 Maret 2019. Dari sana, Fisuar mulai mengetahui banyak tentang komunitas film di Banda Aceh. Mereka kemudian terus bekerja sama dengan Aceh Menonton untuk memutar film-film yang mereka produksi. Fisuar juga mulai menambah anggota dari teman-teman kuliah Faris dan Arif.
Biaya produksi film mereka berasal dari dana mandiri. Menurut penjelasan Faris, film pertama dibiayai oleh Ibu Arif. Setelah berjalan beberapa tahun sejak 2019, dan bekerjasama dengan beberapa komunitas film, mereka mulai berpikir untuk memiliki legal formal untuk bisa mendapatkan dana dari pemerintah maupun lembaga pendanaan untuk produksi film. Baik Arif maupun Faris, juga mendapatkan pekerjaan beberapa kali dengan menjadi clapper board maupun asisten sutradara pada produksi film bersama Aceh Documentary.
Harmoni Dengan Pemerintah Sebagai Siasat Keberlanjutan
Komunitas film di Aceh menyadari bahwa sumber dana dari pemerintah sangat bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan komunitas, selain ada juga sumber dana dari lembaga swadaya masyarakat. Pendanaan dari LSM ini terbilang jarang, dan hanya ketika mereka memerlukan laporan dalam bentuk untuk kegiatan tahunan. Pendanaan dari perusahaan swasta hampir tidak ada.
Oleh karena itu, bagi Faisal komunitas film tidak boleh anti-pemerintah. Karena pemerintah punya sumber dana yang rutin dan bisa dimanfaatkan oleh komunitas film. Di Aceh Documentary, Faisal bertugas membaca peta perpolitikan dan anggaran pemerintah untuk bisa memanfaatkannya sebagai biaya operasional dalam menjalankan program-program di Aceh Documentary.
Faisal juga menilai jika komunitas film tidak harus menargetkan pendanaan film saja, tetapi juga pendanaan untuk kesenian dan kebudayaan. Hal tersebut sudah dijalankan di Aceh Documentary, dimana metode saving selalu diterapkan untuk mengisi kas, dari dana-dana yang didapat.
Kedekatan dengan pemerintah daerah ini terbangun baik dan diikuti oleh komunitas-komunitas film lain di Aceh. Menurut pendapat yang diutarakan Azhari, pemerintah daerah Aceh tidak mempunyai konsep untuk kebudayaan, sehingga jika kita mengkritik karena mereka tidak peduli terhadap komunitas film pun, tidak akan berarti apa-apa. “Mereka (pemerintah) tidak melarang kita (komunitas film) untuk ada, itu bukan masalah. Baru jadi masalah ketika kita dilarang untuk menjadi sebuah komunitas. Oleh karena itu, ketika kita dibantu atau tidak, itu adalah bagaimana cara kita bersiasat” Kata Azhari.
Oleh karena itu, baik Faisal maupun Azhari, memilih untuk mendekati pemerintah dan memberikan masukan-masukan sambil berbenah dan mengikuti birokrasi yang dikehendaki oleh mereka. Langkah ini diikuti oleh komunitas-komunitas film, setidaknya sampai saat ini. Hal tersebut karena melihat perkembangan Aceh Documentary masih bertahan sampai sembilan tahun. Terakhir, dalam konteks UKM kampus, Refanda berharap komunitas Trieng bisa dapat mengikuti setiap pendanaan yang diadakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
AFI 2023 menindaklanjuti hasil penelitian di tiga kota, salah satunya Kota Banda Aceh. Pemilihan kota tersebut berdasarkan riset terkait potensi pengembangan ekosistem perfilman dan keterlibatan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan komunitas. Program Tindak Lanjut disesuaikan dengan riset dan kebutuhan setiap kota. Di Banda Aceh, tim AFI melaksanakan pelatihan penulisan skenario pendek dan tata kelola festival film.
Karya-karya pilihan kota
Banda Aceh
Film tidak lagi dapat diakses karena telah ditayangkan pada Apresiasi Film Indonesia periode tahun 2022.




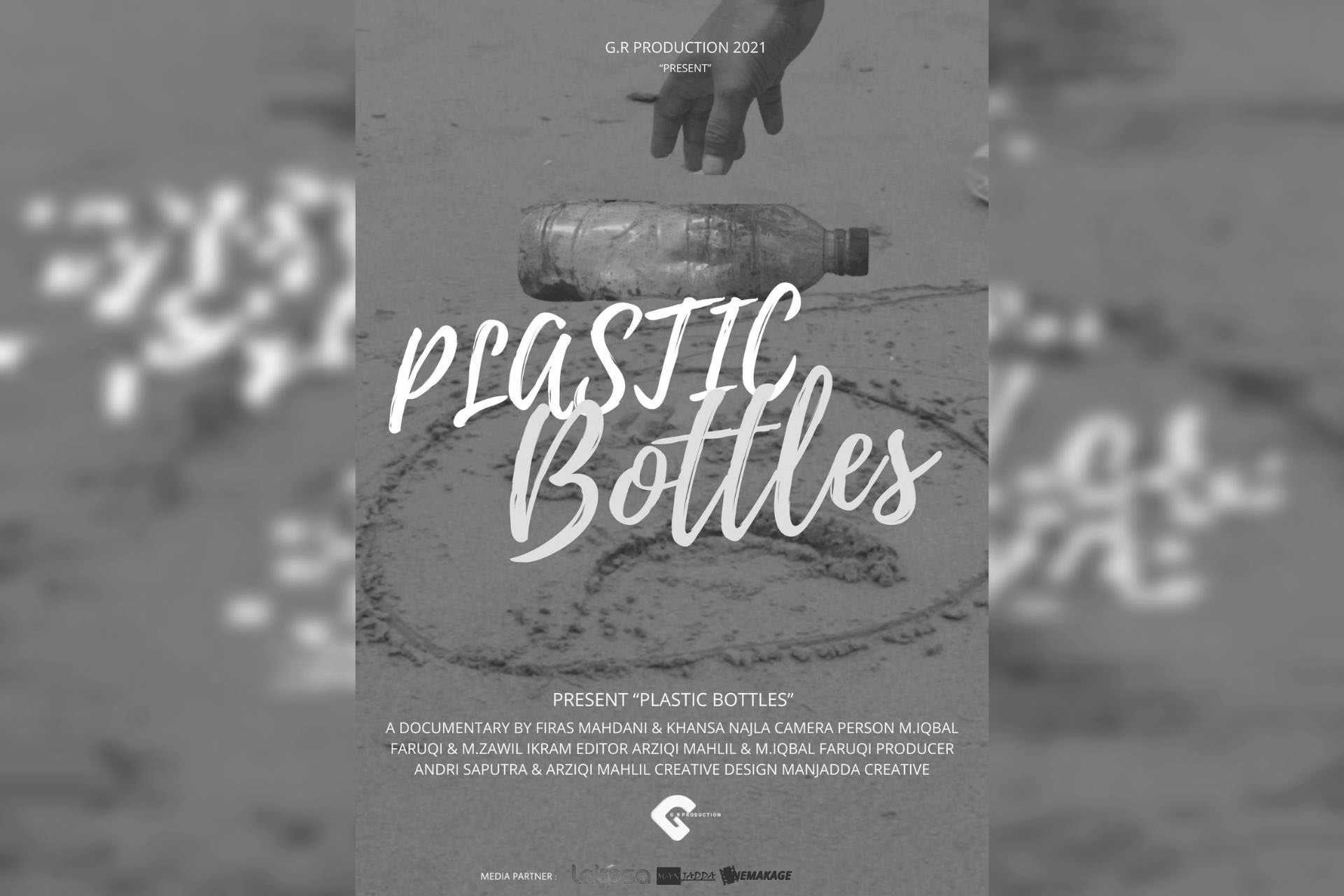
© 2023 Apresiasi Film Indonesia. All Rights Reserved. Bekerjasama dengan Cinema Poetica dan Rangkai.