Kota
Bandung
Judul
Menelusuri Ketakterhubungan dan Ketaksinambungan dalam Komunitas Film Bandung
Penulis
Gorivana Ageza

Waktu menunjukkan pukul 19.12, dan Kedai Cas kian disesaki pengunjung. Santos-Bandung Film Festival (SBFF) memasuki sesi terakhir dalam rangkaian acaranya yang berlangsung selama 20-22 Oktober 2017. SBFF adalah festival yang diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) dengan mempertemukan Santos (Brazil) sebagai kota film dan Bandung sebagai kota desain untuk melakukan kolaborasi pemutaran dengan saling bertukar film asal kota masing-masing. Kedai Cas menjadi lokasi terakhir penyelenggaraan SBFF, setelah sesi-sesi pemutaran sebelumnya dilakukan di tiga tempat berbeda.
Kedai Cas sendiri merupakan kedai kopi milik dua sineas Bandung yang terletak di gang seputaran Jalan Dipati Ukur. Bermula dari kerja sama program antara Kedai Cas dengan beberapa pegiat dari Bandung Film Council (BFC), lahirlah pemutaran film pendek bertajuk Nonton Film di Gang pada pertengahan 2016. Nonton Film di Gang secara rutin diadakan setiap bulan. Dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, Kedai Cas menjelma menjadi tempat nongkrong anak komunitas film Bandung, dan tidak terbatas pada saat gelaran Nonton Film di Gang saja.
Malam itu, 22 Oktober 2017, semua orang berbaur di Kedai Cas. Bagi pegiat komunitas film Bandung, SBFF adalah momen penting. Festival ini berhasil menjembatani dan menggandeng berbagai pihak yang cenderung hanya berkutat di lingkaran masing-masing. Momen itu menunjukkan bagaimana sesuatu yang berbeda dan berasal dari kejauhan, seperti film-film Santos, tidak hanya menyatukan para pegiat, melainkan juga membantu komunitas Bandung menyadari dan memahami dirinya sendiri. Sayangnya, keterhubungan di kalangan komunitas film di Bandung masih jauh panggang dari api.
Ruang Pemutaran, Ruang Pertemuan
Bersamaan dengan berhentinya program Nonton Film di Gang pada 2018, “kemesraan” para pegiat antarkomunitas perlahan luntur. Deden M. Sahid, salah satu sineas yang menginisiasi Nonton Film di Gang meyakini bahwa keberadaan ruang fisik amat signifikan dalam berkomunitas di Bandung. Pandangan serupa diungkapkan oleh Roufy Nasution, seorang sineas Bandung yang karyanya relatif berpengaruh bagi pembuat film dari generasi lebih muda. Ia mengatakan bahwa ada kalanya ia membanggakan era Kedai Cas bak sebuah kisah dongeng.
Setidaknya dalam satu dekade terakhir jumlah ruang pemutaran-diskusi seperti Kedai Cas, dan komunitas ekshibisi di skena komunitas Bandung jauh lebih sedikit ketimbang komunitas produksi. Kesenjangan ini berkaitan dengan situasi skena film Bandung yang didominasi oleh komunitas berbasis kampus—baik berupa program studi maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM) film—yang mayoritas berkutat di ranah produksi. Sementara itu, kegiatan ekshibisi cenderung dikelola oleh komunitas non-kampus, contohnya Bahasinema.
Namun, bukan berarti komunitas berbasis kampus sama sekali tidak melakukan pemutaran film dan apresiasi. Komunitas berbasis kampus yang berfokus hanya pada aktivitas non-produksi, seperti Sinesofia Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, menjadi semacam anomali. Serupa dengan Sinesofia, Liga Film Mahasiswa (LFM) ITB adalah contoh lain dari komunitas berbasis kampus yang beraktivitas di semua lini perfilman, mulai dari produksi hingga apresiasi dan kajian.

Indicinema Bandung. (Obrolan Minggu 1 Perempuan dan Dirinya)
Komunitas ekshibisi sendiri di Bandung dapat dibedakan berdasarkan film-film yang diputarkannya. Pertama, ekshibisi yang berfokus pada film-film lokal Bandung. Sebagai contoh, Ruang Film Bandung lewat program Klinik Film dan pemutaran bulanan Cinemora Open House oleh Cinemora. Berdasarkan penuturan Roufy dari Cinemora, ekshibisi seperti ini umumnya bertujuan untuk memberikan ruang pada pembuat film pemula untuk mempertontonkan karyanya, tanpa perlu dibebani oleh kualitas dan pencapaian estetik.
Kedua, ekshibisi dengan programasi film-film alternatif, seperti yang dilakukan oleh komunitas Bahasinema dan Indicinema. Ekshibisi dengan corak seperti ini cenderung lebih berfokus pada aspek wacana dan kuratorial sehingga asal muasal pembuat film tidak menjadi soal. Ketiga, ekshibisi yang memutarkan film-film panjang. Sebagai contoh, Komunitas Layar Kita. Sepekan dua kali, secara rutin Layar Kita memutarkan dan mendiskusikan film-film panjang (terutama film-film klasik), yang didominasi oleh film luar Indonesia.
Terlepas dari keragamannya, salah satu persamaan dan hambatan mendasar di antara komunitas-komunitas ekshibisi ini adalah mayoritas tidak memiliki ruangan pemutaran sendiri. Komunitas-komunitas ini perlu bekerja sama—dapat juga diartikan dengan “bergantung”—dengan pihak lain yang memiliki ruangan pemutaran. Misalnya, museum milik pemerintah, lembaga kebudayaan asing, galeri seni, resto dan kafe.
Minimnya jumlah komunitas ekshibisi dan ruangan pemutaran menimbulkan keresahan. Kesenjangan antara jumlah produksi film dengan ruang pemutaran berdampak pada keterputusan antara film dengan (calon) penontonnya. Alhasil, komunitas produksi lokal kesulitan mendistribusikan film-filmnya.
Rentetan situasi ini lantas berkenaan dua hal. Pertama, pegiat komunitas, terutama komunitas produksi, cenderung menaruh perhatian lebih pada siapa yang membuat film. Kedua, penonton memiliki kecenderungan untuk lebih memedulikan film sendiri ketimbang siapa pembuatnya. Poin yang terakhir ini dapat dibandingkan dengan hasil pengamatan Roufy pada penonton Sinerame. Sinerame adalah program kerjasama antara Ruang Film Bandung, Co&Co, Cinemora dan sejumlah pihak lainnya, dengan Roufy sebagai juru program. Dalam dua kali gelaran Sinerame, mayoritas penonton dari pemutaran ini berasal dari kalangan umum yang cenderung memusatkan ketertarikan hanya pada film.
Senada dengan Roufy, mantan direktur program Ganesha Film Festival 2018 dan programmer Indicinema, Damar Bagaskoro mencontohkan pemutaran film “Tak Ada yang Gila di Kota Ini” karya Wregas Bhanuteja di Indicinema pada awal 2020. Tiket pemutaran untuk ruangan berkapasitas 50 penonton ludes. Saat itu mayoritas penonton justru berasal dari kalangan umum non-komunitas. Mereka mengetahui film pendek tersebut melalui ulasan media masyhur berbasis daring. Contoh lain, film “Kucumbu Tubuh Indahku” karya Garin Nugroho menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang Indicinema berdiri. Penonton umum mengetahui film tersebut lewat kontroversi yang diangkat oleh media.
Komunitas produksi lantas kebingungan mendistribusikan filmnya. Beberapa memilih untuk membuat pemutaran mandiri tanpa bermitra dengan komunitas ekshibisi. Dalam banyak kesempatan, inisiatif itu hanya dinikmati warga komunitasnya sendiri. Di sisi lain, belum banyak penonton umum yang familiar dengan pemutaran film-film alternatif oleh komunitas
Kondisi ini tentu agak disayangkan. Lewat penonton yang lebih beragam, pegiat komunitas produksi dapat pula bertemu bermacam penilaian penonton dan umpan balik. Dengan menonton karya-karya komunitas lain, suatu komunitas dapat memperoleh perspektif baru dan referensi dalam berkarya. Pertukaran dan perluasan gagasan dimungkinkan. Sebaliknya, publik—termasuk yang belum familiar dengan pemutaran alternatif—pun dapat bertemu dengan berbagai macam tontonan.
Selain contoh kasus Sinerame dan Indicinema, pengalaman komunitas Bahasinema dapat pula dijadikan komparasi. Program-program pemutaran Bahasinema selalu bekerja sama dengan penyedia ruang yang berbeda. Dalam sesi diskusi di salah satu kafe populer di akhir tahun 2018, penonton-penonton yang mayoritas berasal dari segmen pengunjung kafe mengatakan pengalaman itu kali pertama mereka berkenalan dengan film-film pendek alternatif dan mereka menikmatinya.
Yustinus Kristianto, programmer Jogja-NETPAC Asian Film Festival asal Bandung, berpendapat komunitas Bandung cenderung hanya “asyik sendiri” dalam lingkarannya masing-masing. Mahfum bila sosok pegiat komunitas seperti Deden dan Roufy menyayangkan hilangnya Nonton Film di Gang, lantaran keterhubungan antarkomunitas meluntur seiring itu. Sebab, bersamaan dengan hadirnya ruang fisik dan momen, dimungkinkan pula terjalinnya keterhubungan dan kebersamaan.

Sebs Cine Club (Shooting Maybe Someday Another Day But Not Today)
Tak Ada (Menara) Gading yang Tak Retak
Januari 2022 lalu, Coffie (Coordination for Film Festival in Indonesia) memulai rangkaian diskusi publik yang mempertemukan penyelenggara berbagai festival di berbagai kota, dan Bandung menjadi kota pertama. Saat itu hadir empat narasumber yang mewakili empat penyelenggara festival di Bandung: Ganesha Film Festival (Ganffest) ITB, Bandung Independent Film Festival (BIFF)—sebelum dikelola mandiri di luar kampus, BIFF awalnya festival film asal kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)—, Jatinangor Film Festival Universitas Padjajaran, dan International Photography and Short Movie Festival (IPSM) Universitas Telkom. Rupanya dari keempat narasumber hanya Adam yang merupakan pengelola BIFF yang pernah datang ke festival “tetangga”. Ia mengunjungi Ganesha Film Festival. Tiga pengelola sisanya hanya familiar saja dengan festival lainnya.
Terlepas dari pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, ada dua catatan dari diskusi daring itu. Pertama, festival film pada skena komunitas Bandung, sebagaimana komunitas produksi, juga berada pada institusi-institusi pendidikan tinggi. Kedua, pentingnya distribusi pengetahuan baik secara vertikal, yakni dalam komunitas yang sama dari senior ke junior—seperti tugas “safari festival”, maupun secara horizontal yakni antarkomunitas dan antarinstitusi
Kedua hal tersebut berkaitan dengan persoalan keberlangsungan dan sinergi antarkomunitas yang membentuk jejaring dan ekosistem skena film Bandung. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian tulisan sebelumnya, skena Bandung didominasi oleh komunitas berbasis kampus, disertai tendensi keterpisahan dalam jejaring komunitas di Bandung. Kedua kondisi ini dapat lebih dipahami jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa institusi pendidikan memiliki jaminan atas keberlangsungan komunitas sehingga secara kelembagaan komunitas-komunitas ini cenderung beroperasi sendiri-sendiri. Kendatipun ada kerja sama antarkomunitas, sebagian bersifat pendek dan hanya bagian kecil dalam satu acara, alih-alih kemitraan strategis jangka panjang.

Cinemora - Shooting The Boy With Moving Image
Lebih lanjut, komunitas produksi asal Bandung juga amat minim melakukan kerjasama dengan komunitas dari daerah lain. Seperti yang dikatakan Yustinus, kerjasama yang ada bersifat personal yang mana didasarkan pada portofolio individu. Sementara pada ranah ekshibisi, kerjasama komunitas Bandung dengan daerah lain mungkin bisa dihitung dengan jari.
Setidaknya ada empat “privilese” yang dimiliki komunitas berbasis kampus. Pertama, sistem pendanaan yang lebih stabil, yang selanjutnya dilengkapi dengan sistem manajerial pengelolaan komunitas dan mekanisme akuntabilitas. Kemudian, regenerasi pengurus dan anggota yang ajeg. Terakhir, potensi keberlanjutan aspek transfer pengetahuan yang lebih dimungkinkan. Melalui sistem regenerasi yang fungsional, transfer pengetahuan dapat diwujudkan, meski perlu digarisbawahi bahwa itu bukanlah serta-merta.
Regenerasi pada komunitas non-kampus menanggung beban lebih berat karena tidak ada pembaharuan personil secara konstan berkala. Pengelolaan komunitas malah terlalu bertumpu pada personal yang kemudian menjadi sosok “abadi”: ketokohan dan patronasi. Sepintas gaya pengelolaan semacam ini “aman” karena dibayangkan ada perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang, ketimbang pergantian pengelola yang terjadi secara cepat di komunitas kampus.
Namun yang kadang terjadi adalah kegagalan di dua sisi. Perencanaan dan pengembangan jangka panjang tidak berjalan, serta tidak terbentuk sistem pengelolaan yang mapan. Ketika para patron tidak lagi terlampau aktif, komunitas menjadi mandek sementara pengetahuannya bahkan belum sempat didistribusikan. Pun ketika tokoh-tokoh ini tetap aktif, stabilitas rentan tergelincir menjadi stagnasi, bahkan kemunduran, karena nyaris tidak ada regenerasi.
Baik Deden, Yustinus, Roufy, Damar Bagaskoro, maupun Malikkul Saleh (sekretaris jenderal Bandung Film Commission) berpendapat bahwa secara general regenerasi komunitas di Bandung cenderung melempem. Kekhawatiran itu ditujukan pada belum adanya sosok pembuat film dan juru program generasi baru yang menonjol selama beberapa tahun terakhir. Pembaharuan personil tidak serta merta sama dengan kontinuitas perkembangan “output” manusianya. Di skena Bandung, menurut Malikkul, secara general sulit ditemukan orang dengan kemampuan kuratorial yang mumpuni. Akhirnya banyak pemutaran yang kualitas programasinya setengah matang, dan berakhir menjadi kegiatan yang terjadwal saja.
Di ranah produksi, Roufy menandai kecenderungan pembuat film generasi baru justru mengekor karya-karya terdahulu yang sudah lebih dulu masyhur. Roufy melihat pula bagaimana setiap komunitas produksi sudah memiliki gayanya masing-masing yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pembuat film sulit “membebaskan diri” dari pola tradisi tersebut. Konsekuensinya, minim karya-karya yang segar dan memiliki terobosan. Kecenderungan untuk hanya berkutat pada komunitas masing-masing, dan atensi hanya ditujukan pada ranah produksi saja adalah salah satu faktor utama dari situasi ini. Roufy mencontohkan bagaimana ia dulu justru bergabung dengan komunitas non-produksi di luar kampus demi menyaksikan beragam film dan belajar cara membacanya. Deden yang juga merupakan seorang dosen menambahkan bahwa pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan tidaklah cukup jika tidak disertai pengalaman riil belajar secara langsung “lapangan”.
Eksistensi dalam Dunia yang Diisolasi
Dari sebuah kotak dus muncullah seorang anak laki-laki. Seiring waktu ia mulai bertanya-tanya meratapi eksistensinya “…mengapa aku harus seperti mereka? … aku mencari sesuatu yang tidak aku ketahui…”. Ia menyaksikan kehidupan manusia-manusia lain beserta segala konflik dan krisis eksistensialnya. Ia pun menghindari interaksi dengan mereka. Anak laki-laki ini lantas memilih berlari pulang “meninggalkan dunia” untuk kembali ke dalam kardus.
Demikianlah penggalan adegan dalam film “Whispering Box” (2014) karya Irvan Aulia. Irvan Aulia adalah nama yang disebut-sebut oleh Yustinus dan Roufy sebagai salah satu sutradara muda yang karyanya memiliki kekhasan dan berdampak pada generasi selanjutnya, bersanding dengan Bihar Jafarian, Prama Yodha, Gilang Bayu Santoso, Gerry Fairus, Mustafa, dan Roufy sendiri. Kisah dalam film “Whispering Box” menjadi gambaran, sekaligus pula afirmasi, atas tendensi komunitas Bandung yang gemar berjibaku hanya pada “kardus” (baca: lingkaran)-nya masing-masing.
Tendensi untuk berkutat hanya pada lingkup hidup “mikro” (personal, domestik, cakupan kecil) merembesi narasi-narasi dalam film komunitas Bandung. Kisah-kisah ini seperti mereka ulang kebiasaan hidup dalam “menara gading” masing-masing komunitas sehingga berjarak dari kompleksitas kenyataan. Hal ini kemudian terwujud dalam isu yang diangkat dan digambarkan dalam film, dan bagaimana problematika itu disikapi dan diselesaikan oleh tokoh dalam film.
Damar Bagaskoro menambahkan bahwa film komunitas Bandung bercorak apolitis. Konflik yang hadir dalam narasinya seperti dicabut dari realitas dan absen konteks sosial. Pun ada kecenderungan untuk mengisolasinya dalam lingkup domestik, seakan-akan sama sekali tidak ada keterkaitan dengan dunia di luarnya.
Secara umum ada penutup atau “solusi yang memuaskan” atas konflik diangkat oleh film. Situasi ini dapat terjadi karena keengganan untuk mendekati dan/ atau kegagalan pembuat film dalam memahami carut-marutnya realitas. Akibat kenyataan yang disimplifikasi—hanya melihat hal yang di permukaan dan familiar—, maka persoalan seakan-akan dapat diselesaikan dengan cara yang mudah saja. Malikkul mengamini pendapat Damar yakni film-film Bandung cenderung belum memiliki kedalaman isu. Sementara Yustinus mengaitkannya dengan sejumlah karakteristik, yakni (1) gaya populer dan membicarakan hal-hal di permukaan; (2) kecenderungan narasi inspiratif (motivasional) dan sugar coating; (3) reproduksi nilai normatif arus utama.
Pendapat-pendapat tersebut, terutama dari Damar dan Yustinus kian menegaskan kecenderungan untuk mengedepankan aspek internal (saya dan kelompok-saya). Seolah-olah kesulitan hidup yang dialami oleh seseorang hanya terkait dengan dirinya saja, dan individu bukanlah bagian dari dunia. Secara implisit hadir keyakinan bahwa merupakan tanggung jawab individu untuk mengembalikan kekacauan pada kondisi ideal. Persoalan dan “bencana” adalah konsekuensi (“hukuman”) dari kegagalan individu. Narasi ideal inspiratif muncul seiring dengan “kesabaran” tokoh melewati masalah, sambil tetap mempertahankan moralitasnya yang hitam-putih, alih-alih terkontaminasi kemuskilan realitas. Di titik ini—terutama jika kembali mengacu pada pendapat Yustinus—menjadi kentara bahwa sekalipun diproduksi oleh komunitas, film alternatif Bandung cenderung tidak mengarah pada pembentukan wacana alternatif.
Lebih lanjut, tendensi untuk menghindari kompleksitas keadaan tidak hanya muncul dalam narasi filmnya, melainkan juga muncul dalam ruang-ruang pemutaran dan diskusinya. “… mereka tidak punya latar belakang programasi ekshibisi yang memadai, jadi mereka bikin pemutaran yang tanpa programasi … baik itu yang dilakukan komunitas di dalam kampus maupun di luar kampus. … lebih ngepop … kurang serius … mungkin itulah ciri khas Bandung. Bandung tuh gak mau mikir yang terlalu susah-susah, gak mau dalem-dalem mikirnya, jadi ya seru-seruan aja,” demikian Malikkul menjelaskan gaya ekshibisi di Bandung.
Sementara itu Roufy menjelaskan pendekatan yang ia ambil melalui Cinemora Open House sehingga pemutaran rutin bulanan yang baru dimulai tahun lalu ini hampir selalu penuh sesuai kapasitas maksimal penonton. Ketika di saat bersamaan, akibat pandemi, justru banyak ruang pemutaran yang non-aktif.
“… itu selalu full aja, bayar tiket pun sepuluh ribu. Ketika aku buat screening itu memang ada perubahan ambience yang aku coba, gimana waktu diskusi itu jangan serius … duduk bersila, ruangnya akrab banget, deket, kita sama penonton tuh deket karena saung. Jadi mereka merasa cair juga. …. Filmnya serius tapi dibawa becanda .. aku rasa kultur di Bandung tuh bodor, jangan terlalu serius-serius banget. Kalo ada orang serius di Bandung kayanya malah dicengin … Kayanya orang di sini gak bisa dibawa terlalu serius…”
demikian penjelasan Roufy mengenai “resep suksesnya”. Lewat penuturan Malikkul dan Roufy, serta pendapat Deden dan Yustinus, secara tersirat ada anggapan yang bersifat dualistik, yakni antara sesuatu yang “seru dan ringan populer” dengan sesuatu yang "serius, mikir dalem, dan rumit”. Oposisi ini analog dengan gambaran yang ditunjukkan oleh film “Whispering Box”

4 GA Production - (Shooting Words)
Dalam pengamatannya pada film-film pendek komunitas Bandung yang dirilis pada tahun 2019-2020, Damar mencatat ada empat corak cerita yang dominan: (1) horor, (2) elemen imajiner yang menginterupsi realitas, (3) konflik domestik yang terisolasi, umumnya terkait figur paternalistik, (4) gaya absurd (“Roufy-isme” dan para filmmaker yang terinspirasi olehnya).
Dari catatan Damar tersebut, kisah tentang elemen imajiner yang menginterupsi realitas, pun isolasi konflik pada ruang domestik, seperti kembali mengafirmasi adanya pola untuk “memalingkan” diri dari kompleksitas kenyataan atau upaya pemberian solusi pintas. Sementara pola narasi yang berpusat pada figur paternalistik berkenaan dengan tidak hanya dengan tendensi mengawetkan moralitas normatif, melainkan juga mengisyaratkan corak patronasi.
Dalam film “Loper” (2013) karya (alm) Dendie Archenius dikisahkan ada seorang suami yang tanpa sengaja menerima koran “ajaib” dari masa depan. Dalam surat kabar itu termuat berita bahwa akan terjadi malapetaka di rumahnya, dan ia menjadi korbannya. Alih-alih melarikan diri ke luar rumah, ia justru semakin mengurung diri di rumah dan berwaspada untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Malam itu, pelaku yang berniat jahat muncul: istri dan teman perempuannya. Setelah serangkaian upaya membela diri, sang suami selamat, sementara istri dan temannya tewas. Pagi harinya semua nampak baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa di rumah itu. Sang suami akhirnya membuka pintu pagar. Ia berdiri di ambang batas antara area teras rumahnya dengan jalanan demi berbincang dan berterima kasih kepada sang loper koran.
Film “Loper” yang menjadi official selection Ganffest 2014 secara tersirat sudah mengamini argumen Damar. Sekalipun berdiam diri dalam lingkaran masing-masing membahayakan bagi keberlangsungan dan perkembangan individu dan komunitasnya sendiri, pola tersebut masih tetap menggejala di skena komunitas film Bandung.
Semangat Membara, Minim Rencana
Kesamaan minat pada film merupakan alasan utama dari terbentuknya komunitas-komunitas ini. Di samping itu, adapun alasan profesional, misalnya pada mahasiswa kampus jurusan film dan rumah produksi. Minat (“passion”) adalah bahan bakar untuk memulai dan menggerakkan sesuatu.
Namun, tentu minat saja tidak cukup. Damar misalnya membuka diskusi mengenai banyaknya pegiat yang “berguguran” dari komunitas, serta komunitas atau kegiatan yang “gulung tikar” lewat sebuah pertanyaan “apakah memang naturnya seperti itu, atau itu mismanajemen?”. Sementara Malikkul mewanti-wanti bahwa komunitas tidak bisa hanya mengandalkan “seru-seruan” saja, karena dalam pengelolaan diperlukan komitmen dan kemampuan manajerial. Ia menambahkan, komunitas akan sulit dikelola jika hanya mengandalkan (sisa) waktu luang dari anggotanya.
Jika membandingkan pandangan dari Damar dan Malikkul dengan pola regenerasi di skena komunitas Bandung, ada benang merah. Dalam konteks pegiat komunitas film dari kalangan mahasiswa, beberapa tidak melanjutkan beraktivitas di komunitas setelah menamatkan studinya. Orang datang silih berganti di komunitas kampus. Ketika pelajar tersebut sudah terjun ke dunia kerja, maka tuntutan untuk berkomitmen pada komunitas menjadi semacam beban ganda. Tidak sedikit pula pegiat komunitas Bandung yang lantas memilih untuk berpindah ke Jakarta karena alasan pekerjaan, baik masih dalam ranah yang berkaitan dengan perfilman maupun bidang yang berbeda. Ibukota, yang hanya berjarak dua jam dari Bandung, masih dianggap lebih “menjanjikan”.
Malikkul maupun Deden adalah pengurus dari Bandung Film Commission (BFC)—komisi film daerah yang juga berfungsi sebagai penghubung komunitas-komunitas di Bandung—yang berdiri Maret 2019. Meski demikian keduanya menyadari bahwa BFC belum berfungsi maksimal sebagai “hub” (penghubung antarkomunitas) karena lembaga sendiri tidak memiliki pendanaan dan pengurusnya tidak bisa total mencurahkan waktu dan fokus lantaran “… masih sibuk dengan periuk nasi nasing-masing”.
Berdasarkan pengamatannya, Malikkul berusaha menjabarkan “kekeliruan manajerial” yang kerap terjadi dalam pengelolaan komunitas. BFC pun bukan pengecualian. Manajemen komunitas terlalu bertumpu pada “passion” dan momen-momen “eventual”. Pada praktiknya, komunitas bekerja secara impulsif sporadis, serta tidak memiliki visi jangka panjang berkesinambungan. Perencanaan (termasuk rencana pelaksanaan), sistem kerja, strategi, serta nilai dan target tidak terjelaskan. Dan terakhir, minimnya orang yang berkomitmen melaksanakannya.
Yustinus menyayangkan disfungsinya lembaga yang dibentuk guna menghubungkan dan mewadahi komunitas-komunitas film di Bandung. Ia mengingatkan, jika lembaga representatif gagal menjadi “payung” yang menaungi, maka akan membuat komunitas-komunitas di bawahnya, pada akhirnya tetap berusaha masing-masing.
Sebagaimana contoh kasus Kedai Cas, dari contoh kasus BFC—yang pengurusnya rata-rata adalah “perwakilan” dari komunitas-komunitas di Bandung—iktikad untuk saling terhubung satu sama lain pun tidak cukup akibat ketiadaan “logistik”: dana dan ruang fisik yang dapat dijadikan ruang aktivitas bersama di lokasi strategis. Seperti yang digelisahkan Deden “… logistik gak ada cuma mengandalkan semangat”. Aktivitas pada skala kecil mungkin terselamatkan lantaran dana bukanlah faktor dominan. Di sini modal sosial (akses pada sumber daya manusia dan jejaring) lebih penting. Namun, “pada skala kerja yang lebih besar dan mutakhir, tidak bisa tanpa dana…”, demikian tegasnya.
Kondisi menjadi lebih pelik pada komunitas di luar kampus. Pada satu pihak, komunitas dituntut untuk mampu membiayai operasionalnya. Di saat bersamaan, para pegiatnya mesti membiayai ongkos—tidak hanya uang, melainkan juga waktu dan tenaga—keterlibatannya dalam aktivitas komunitas. Padahal, pertama-tama, pegiat—khususnya mengacu kepada mereka yang sudah bekerja—mesti pula mencari nafkah untuk kebertahanan kehidupannya. Tidak mengherankan jika banyak mahasiswa yang berhenti dari aktivitas komunitas ketika sudah terjun ke dunia kerja. Dari sini dapat dipahami mengapa ada pola “come and go”.
Lebih lanjut, keterputusan juga menggejala di skala yang lebih besar yakni antara komunitas dengan pemerintah. Di titik ini, BFC berada pada posisi yang tidak mudah karena sekalipun memosisikan diri sebagai “konektor” (penghubung, mediator) posisi tawar yang dimilikinya relatif rendah. Kebijakan, termasuk juga pendanaan dan fasilitas, yang disediakan oleh pemerintah kerap kali tidak tepat guna. “Pemerintah lack of knowledge and less inisiative … pemerintah kurang mendengarkan komunitas … tidak sesuai kebutuhan karena tidak minta saran…”, demikian kekecewaan Malikkul. Keresahan lainnya muncul dari Yustinus perihal ketidakmerataan dukungan material dari pemerintah. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan pemerintah terhadap kondisi skena, sehingga menimbulkan “kesalahpahaman”. Pemerintah dianggap “mesra” dengan komunitas-komunitas tertentu saja.
Pandemi Memisahkan, Internet Menyatukan
Pandemi COVID-19 telah mengubah kondisi skena komunitas film di Bandung. Berbagai komunitas, terutama komunitas berbasis kampus, memindahkan aktivitasnya ke ruang virtual. Festival film seperti Ganffest 2022 diselenggarakan secara daring, sedangkan BIFF menunda waktu penyelenggaraannya selama setahun menjadi Juli 2022. Sejumlah kegiatan pemutaran alternatif—termasuk lembaga swasta yang bekerja sama menyediakan ruangan pemutaran— berhenti beroperasi akibat pandemi. Bahkan ketika pandemi sudah terkendali dan berbagai kegiatan luring kembali dimungkinkan, bioskop alternatif seperti Indicinema masih belum aktif kembali. Secara kontras, seperti yang dituturkan Deden, pandemi telah membuat rumah-rumah produksi justru kebanjiran tawaran pekerjaan. Tingginya permintaan akan konten audio-visual seiring dengan semakin masifnya aktivitas di dunia digital
Beberapa tahun terakhir, dan kemudian mencapai puncaknya ketika pandemi, memperlihatkan bagaimana media sosial dan algoritma memiliki andil signifikan dalam menyebarluaskan informasi pemutaran alternatif. Sinerame yang dimulai per Juli 2022 menunjukkan tren baru, yakni kehadiran penonton dari kalangan umum (bahkan berasal dari luar Kota Bandung) yang mengetahui kegiatan pemutaran film lewat informasi internet. Agaknya tidak beroperasinya bioskop berjaringan di pusat-pusat perbelanjaan untuk waktu yang relatif panjang akibat pandemi telah menggeser kebiasaan penonton. Ketersebaran film-film alternatif di internet membuat khalayak melirik tayangan film di luar bioskop arus utama.
Terlepas dari konsekuensi yang dibawa oleh algoritma, internet mengeksplisitkan cara kerja jejaring: menghubungkan dan menyinkronkan hal-hal yang sebelumnya terpisah. Komunitas-komunitas Bandung yang cenderung terpisah-pisah, berkutat dalam lingkarannya masing-masing, dan tidak sinergis barangkali perlu mereorientasi cara kerjanya. Komunitas sendiri menyiratkan adanya keterhubungan kolektif antar pihak secara sinergis, termasuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dalam mengupayakan keterhubungan dan kesinambungan, kemampuan untuk melihat relevansi mutlak diperlukan dalam berkomunitas maupun berkarya; bahwasanya berbagai hal saling terhubung, memengaruhi, dan berdampak.
Karya-karya pilihan kota
Bandung
Film tidak lagi dapat diakses karena telah ditayangkan pada Apresiasi Film Indonesia periode tahun 2022.



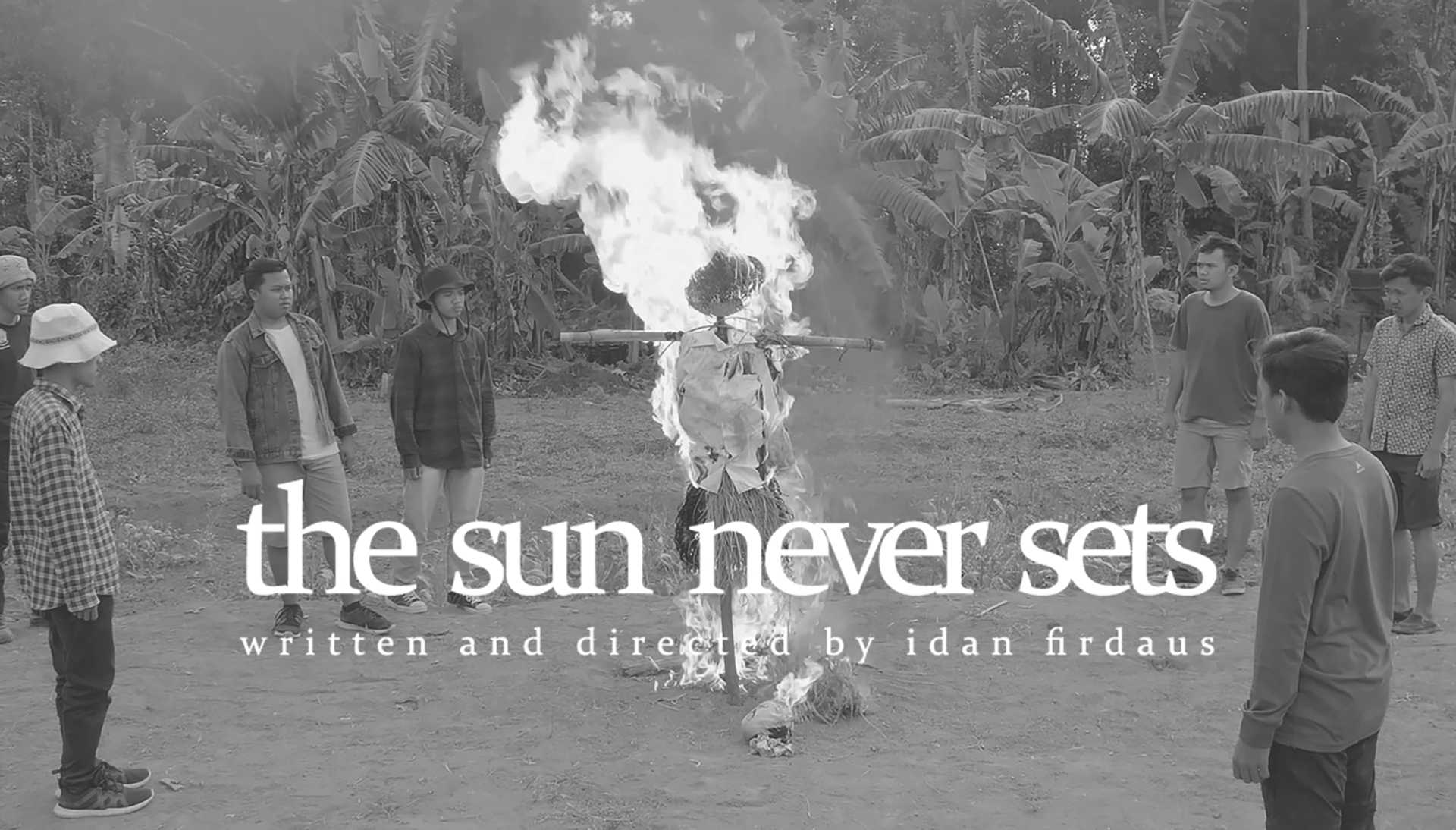

© 2023 Apresiasi Film Indonesia. All Rights Reserved. Bekerjasama dengan Cinema Poetica dan Rangkai.