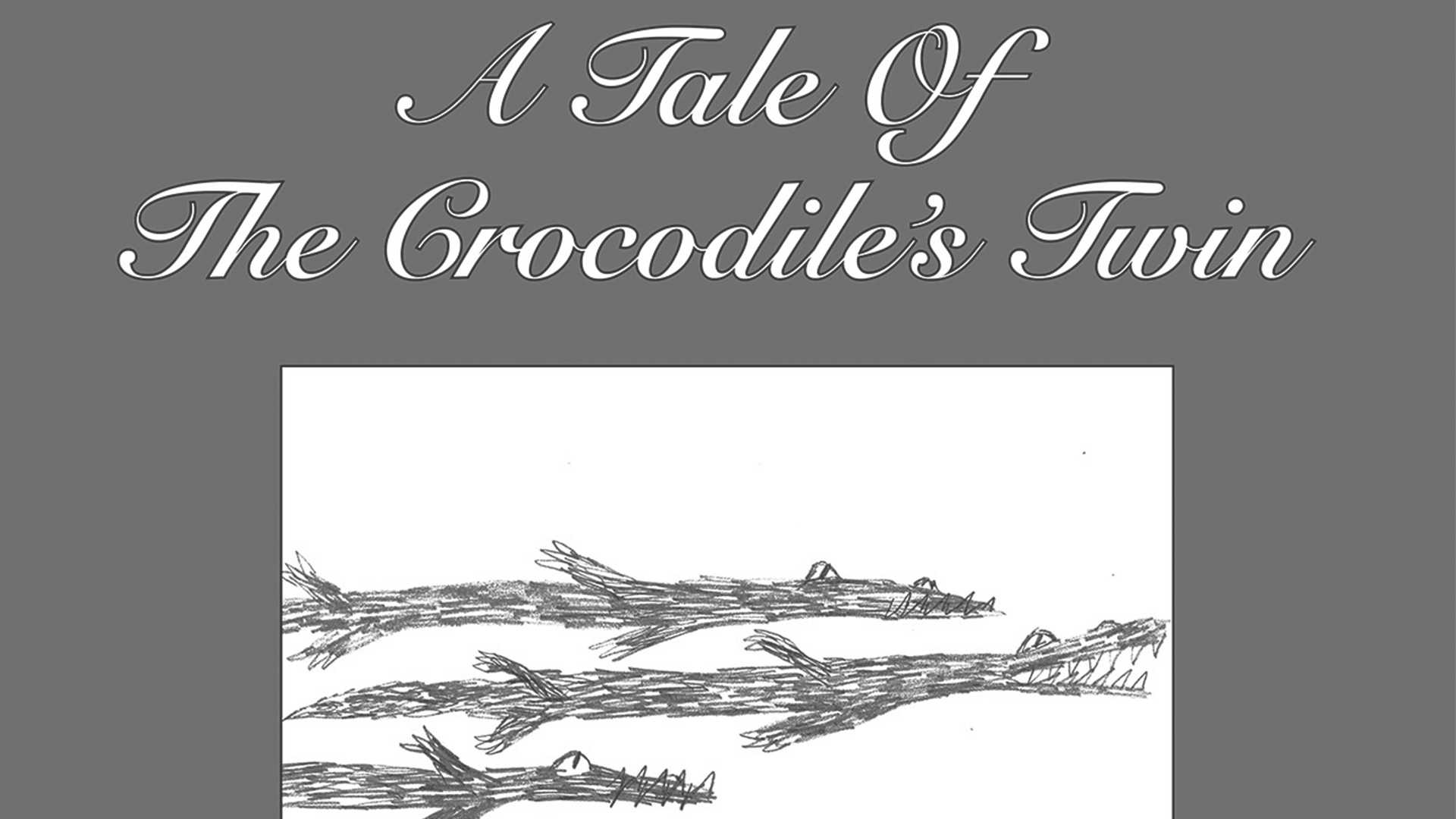Semua orang bisa membuat film jika dibutuhkan. Pernyataan ini mungkin terdengar berlebihan, tapi demikianlah medium film diartikulasikan oleh berbagai komunitas di Palu, daerah yang jauh dari industri perfilman yang mapan. Kemajemukan komunitas di Palu dihuni oleh beragam kebutuhan dan dieratkan oleh film sebagai medium aktivismenya. Bermula dari komunitas literasi perpustakaan Nemubuku yang didirikan pada tahun 2007, muncul kegiatan rutin menonton film yang kemudian menjadi Bioskop Jumat pada tahun 2009.
Bioskop Jumat lahir di tengah ketiadaan bioskop komersial yang tutup pada tahun 2000. Secara rutin, Bioskop Jumat melaksanakan pemutaran dan diskusi film di teras samping rumah komunitas. Dalam sekali pemutaran, rata-rata ada sekitar 25 penonton yang terdiri dari anggota komunitas dan khalayak umum. Di Bioskop Jumat siapa pun boleh menawarkan film untuk ditayangkan. Sumber film bisa dari mana saja dan penayangannya selalu gratis, karena tujuannya untuk belajar.
“Kami pernah ditegur oleh salah satu rumah produksi asal Jakarta karena ketahuan memutarkan film mereka tanpa izin. Tapi meski begitu, saya yakin bahwa kultur produksi dibangun dari kultur menonton,” ucap Neni Muhidin, peneliti sekaligus perintis Bioskop Jumat.
Selama mengelola Bioskop Jumat, Neni melibatkan teman-teman pegiat lain. Soraya Pinta Rama, penulis di beberapa media lokal, membantu sebagai manajer sekaligus programmer. Setelah itu ada Syukuran atau Onqi, yang kemudian menjadi editor beberapa film pendek seperti Umar Amir (2013) dan WC Terbang (2017). Lalu ada Yusuf Radjamuda atau Papa Al, sebagai proyeksionis Bioskop Jumat, yang nantinya menjadi sutradara film Halaman Belakang (2013) dan Mountain Song (2019). Terakhir, ada Eldiansyah Latief atau Ancha, sutradara film Umar Amir.

Pemutaran film Tonny Trimarsanto oleh Nemu Buku di 2019.
Bioskop Jumat juga berjejaring ke luar Palu untuk memperkaya kuratorial filmnya. Forum Lenteng di Jakarta berkontribusi lewat DVD Untuk Semua—program penerjemahan film-film penting dalam sejarah sinema. Sementara Elida Tamalagi, yang menginisiasi Kinoki di Yogyakarta, juga berpartisipasi dengan memberikan sejumlah arsip film. Bioskop Jumat juga pernah bekerja sama dengan distributor film, seperti Kolektif Film dan Buttonijo. Beberapa program pemutarannya dibuat berbayar untuk mendukung ekosistem film komunitas, dengan harga tiket menonton paling mahal 15 ribu Rupiah.
Perubahan dari gratis ke berbayar tidak lantas menurunkan minat para penonton. Pasalnya, sebelum kehadiran Bioskop Jumat, kultur menonton berbayar sudah dibentuk oleh Bazar Film yang menayangkan film-film box office seperti Ayat-Ayat Cinta (2008). Pelaksana menyewa ruang yang mirip fasilitas bioskop komersial, semisal gedung pertunjukan milik Radio Republik Indonesia. Penonton yang datang diduga ribuan, dari segala penjuru kota dan kabupaten. Namun, meski antuasiasme menonton terlihat besar, bioskop baru kembali buka di Palu hampir satu dekade setelahnya, tepatnya pada tahun 2017.
Komunitas yang Lahir dari Ruang Film
Sebagai orang yang suka menggambar dan pernah membuat film, saya turut bergabung dengan Bioskop Jumat setelah lulus SMA. Hampir setiap malam saya ke sana. Pada saat itu, Bioskop Jumat memungkinkan saya untuk sekadar duduk sambil membuka laptop tanpa harus memesan makanan atau minuman. Di sana saya berjumpa dengan orang-orang yang sefrekuensi, termasuk mereka yang juga suka menggambar.
Alhasil, pada tahun 2014, kami membentuk Serrupa—komunitas seni visual yang berfokus pada isu-isu kontemporer. Serrupa kerap membantu mengerjakan kebutuhan visual, seperti poster film dan publikasi kegiatan pemutaran. Pada tahun 2016, Serrupa berevolusi menjadi Forum Sudutpandang—kolektif seni interdisiplin yang mengelolah program-program seperti pameran dan residensi seni, pertunjukan musik, lokakarya, produksi, dan pemutaran film. Saat ini, Forum Sudutpandang beranggotakan 27 orang.
Forum Sudutpandang memiliki platform ekshibisi yang diberi nama Klub Penonton. Film-film yang diputar biasanya datang dari distributor skala komunitas atau langsung dari sutradaranya atas asas pertemanan. Sebagai komunitas interdisiplin, Forum Sudutpandang sering menyajikan format pemutaran film di ruang-ruang kolaboratif, semisal dalam rangkaian festival yang di dalamnya terdapat pasar, musik, kuliner, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mempertemukan film dengan penonton dan ruang-ruang lebih kompleks.

Produksi film Saya di Sini, Kau di Sana oleh Forum Sudutpandang di 2021
Forum Sudutpandang juga memproduksi beberapa film—sebagian besar dokumenter—di antaranya Our Last Mangrove (2019), Documentation of Survivors and Eyewitnesses Stories Tsunamis in Central Sulawesi (2022), A Tale of the Crocodile’s Twin (2022), dan Tanah Emas (2022). Pada tahun 2023, Forum Sudutpandang mendapat fasilitasi dana kebudayaan sinema mikro untuk mengadakan program pemutaran film yang bertajuk Timur Raya Sinema. Pemutaran layar tancap ini dilaksanakan di enam lokasi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi selama dua bulan. Film-film yang diputar berasal dari jaringan komunitas di Indonesia Timur, yakni Makassar, Samarinda, Kupang, dan Papua. Selama pelaksanaannya Forum Sudutpandang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang berlokasi di tempat pemutaran. Total jumlah penonton mencapai 1.000 orang, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Donggala.
Besarnya antusiasme penonton di kota atau kabupaten sekitar Palu merupakan hal yang penting untuk digarisbawahi. Sebab, ekosistem film di Palu sesungguhnya tidak bisa dibaca hanya dalam lingkaran kawasannya. Di Sigi, misalnya, terdapat Bioskop Todea yang diinisiasi oleh Dinul dan Zikran di Sigi pada tahun 2022. Bioskop Todea memiliki program regular sebulan sekali, baik dibuat sendiri maupun berkolaborasi dengan komunitas lain. Format pemutarannya sebagian besar berupa layar tancap, gratis, dan swadaya—memutarkan film-film dari Palu, Sigi, dan Donggala.

Pemutaran Film Festival Agroforestri oleh Komunitas Bioskop Todea di 2022
Sementara itu di Donggala, tepatnya di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, terdapat Yayasan Tana Sanggamu yang aktif sejak tahun 2018. Didirikan oleh Ade Nuriadin, Yayasan Tana Sanggamu merupakan komunitas anak muda yang bergerak di bidang pertanian, media, dan pengembangan, wirausaha sosial – yang menggunakan film untuk mendistribusikan pengetahuan-pengetahuan. Menurut Ade, memutar film di desa jauh lebih mudah daripada di kota. Penonton di desa, berdasarakan amatannya, cenderung memiliki motivasi menonton yang lebih besar.
“Donggala sendiri sudah mempunyai kultur menonton itu, karena dulu pernah ada bioskop lokal di sini,” ucap Ade Nuriadin
Ade Nuriadin sendiri punya pengalaman cukup panjang di ekosistem film. Ia pernah menjadi direktur dan kurator di program South East Asia Movie Open Program Yogyakarta pada tahun 2017, dan pernah terlibat di beberapa produksi film, salah satunya sebagai kru dan pengisi suara di Worked Club (2015) karya Tunggul Banjaransari. Pada tahun 2014, Ade juga menjadi partisipan lokakarya SEAScreen Academy di Makassar. Di Palu, Ade menjadi penulis film WC Terbang, produser Home Sweet Home (2019) karya Muh. Ifdhal dan Senandung Bunga dari Bulukadia (2023) karya Eldiansyah Latief, serta sutradara film Tanigasi (2022)—dokumenter pendek tentang upaya warga desa dalam menghindari krisis pangan pasca-bencana.

Produksi film Tanigasi oleh Komunitas Tana Sanggamu di 2021.
Tentunya, tak semua film di Palu dibaluti dengan semangat aktivisme. Arul dari komunitas Nadoyo Production, misalnya, lebih tertarik untuk menarasikan keseharian di Palu sebagai film hiburan. Beranggotakan 12 orang, Nadoyo Production dihuni oleh orang-orang dengan latar belakang berbeda, dari anak teater, musisi, pedagang, pekerja IT, hingga aparat sipil negara. Saat menyusun cerita film, mereka saling mengintervensi dan melempar ide yang kemudian dijahit menjadi satu cerita film dengan balutan komedi.
“Salah satu hal yang kami eksplorasi menjadi unsur komedi adalah keragaman bahasa dan aksen masyarakat lokal di Palu. Kami tidak terlalu fokus pada pesan di film. Mau ada pesan atau tidak, itu bukan hal yang ingin kami capai melalui film,” Kata Arul.
Sampai saat ini Nadoyo Production telah memproduksi sekitar 20-an film dengan durasi 5 sampai 30 menit. Dana produksinya dihimpun secara swadaya dan sponsorship. Mereka mengelola ekshibisinya secara mandiri dengan format pemutaran layar tancap gratis di desa-desa atau menyewa gedung yang biasa dipakai untuk pemutaran, seperti gedung taman budaya—sebelum akhirnya sudah hancur karena tsunami. Pemutaran bernama Nadoyo Sinema tersebut dihargai dengan tiket masuk 25 ribu rupiah. Diselenggarakan selama maksimal lima kali pemutaran dalam seminggu, total penonton harian bisa mencapai 600 orang. Setelahnya, film-film tersebut diunggah ke YouTube, dan di-monetize.

Pemutaran film oleh Komunitas Nadoyo dilakukan selama tiga malam berturutturut. Berlokasi di Gedung Teather Taman Budaya Kota Palu di 2015.
Regenerasi Sineas dan Respons Terhadap Bencana Alam
SMA saya, SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu, merupakan salah satu sekolah yang memasukkan film ke intrakurikuler kelas 12. Meski dibuat untuk mata pelajaran, film-film yang dibuat tidak pernah dikompetisikan, dan hanya menjadi hiburan sebelum perpisahan. Murid-murid hanya disuruh memanfaatkan fasilitas multimedia di sekolah. Film yang diproduksi kemudian ditayangkan di laboratorium komputer secara berbayar untuk menambah biaya perpisahan sekolah. Pendeknya, film saat itu tidak dituntut menjadi karya yang serius. Baru ketika Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) hadir, pelajar mulai mendapat dorongan lebih.
FLS2N melahirkan sejumlah nama baru, seperti: Sarah Adilah, sutradara Cermin (2015), Neraka di Telapak Kaki (2018), dan Boncengan (2020); Nur Amri Firmansyah, sutradara Yang Hilang dan Yang Tumbuh (2022); Fauzan Kurnia Muttaqin, sutradara film Tugas Akhir (2022); Vania Qanita Damayanti, sutradara film Telur (2021); dan Fikri Suni. Nama-nama tersebut sebagian besar masih aktif berkegiatan film. Fikri, Amri, dan Vania mendirikan AHERA Films. Sementara Sarah, bersama sejumlah pegiat film lain, mendirikan Sinekoci.

Komunitas sekoci melakukan workshop development story untuk anak magang SMK Negeri 2 Palu di 2022
Sinekoci menarik untuk dibahas lebih jauh, karena produktivitasnya dalam merespons dan menanggapi darurat kebencanaan melalui film. Pada 2020-2022, Sinekoci menginisiasi proyek dokumenter partisipatif Hidup dengan Bencana yang melibatkan empat komunitas interdisiplin. Proyek itu menghasilkan 5 film dokumenter pendek yang membicarakan konteks kebencanaan di Palu melalui perspektif yang kontekstual dengan wilayah tempat komunitasnya berada. Film-film yang diproduksi adalah Turun ke Atas (2022) produksi Nemubuku; Saya di Sini, Kau di Sana: A Tale of the Crocodile’s Twin (2022) produksi Forum Sudutpandang; Tanigasi (2022) produksi Yayasan Tana Sanggamu; dan Timbul Tenggelam (2022) produksi Sikola Pomore. Film-film ini pertama kali ditayangkan pada 2022 dalam rangka peringatan empat tahun peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, serta Donggala. Selain proyek dokumenter, Sinekoci juga memproduksi fiksi pendek Pada Suatu hari (2020) yang juga masih dalam motif melestarikan pengetahuan lokal tentang kebencanaan.
Peristiwa kebencanaan pada tahun 2018 begitu penting untuk diangkat dalam bentuk film. Pasalnya, tidak hanya menghancurkan infrastruktur kota, bencana tersebut juga menggoyahkan keyakinan tentang wilayah yang selama ini ditinggali. Ada begitu banyak pengetahuan penting yang gagal terdistribusi, dan hanya tersimpan dalam syair lisan, mitos, cerita rakyat, dan nama-nama terdahulu sebuah lokasi. Peran komunitas lantas menjadi penting untuk terus membicarakan peristiwa tersebut menggunakan medium-medium yang mudah didistribusikan, diakses, dan diapresiasi oleh publik.
“Setelah bencana orang-orang mempertanyakan hal yang mungkin ia tidak pernah pertanyakan sebelumnya tentang tempat ia tinggal,” ucap Neni Muhidin.
Ketidakhadiran institusi formal dan ekosistem perfilman yang mapan di Palu mungkin memberikan celah pengetahuan. Namun, pada saat bersamaan, hal tersebut juga menciptakan keleluasaan dalam menyikapi medium film. Film lantas terdekonstruksi dari nilai asalnya, lalu direfleksikan, didiskusikan, dan diuji kembali dengan nilai-nilai yang baru. Di sini, peran komunitas setempat menjadi penting. Di Palu, komunitas memberikan muatan baru pada film sesuai kebutuhannya, dari aktivisme hingga hiburan. Meski begitu, pasca-bencana tahun 2018, satu hal yang terjadi secara kolektif adalah film mampu digunakan sebagai pencatat dan alat tutur kebencanaan.
Catatan Kuratorial Kota Palu
oleh Alexander Matius
Pasca serangkaian gempa dan tsunami, film-film dari Palu dan wilayah sekitarnya menjadi punya peranan penting dalam proses perkenalan budaya dan mitigasi bencana. Masyarakat telah hidup dalam pusaran bencana yang sewaktu-waktu dapat tiba, seperti gempa bumi yang telah tercatat jauh sebelum mulai ditinggali. Inisiatif pembuat film guna menyadarkan Kembali apa yang sesungguhnya mereka tinggali adalah keputusan krusial yang akan berdampak baik. Film-film dari Palu memulai dari dasar Kembali: menelusuri jejak-jejak kehidupan masa lampau, merisetnya, membedah dampak-dampaknya, menceritakannya Kembali lewat berbagai bentuk, sehingga bisa tersebar dan tersimpan; sehingga nantinya tidak mengulangi dari awal pencarian-pencarian hidup Bersama bencana yang berimbas pada persiapan, ketahanan, dan ketangguhan. Ada lima film yang dipilih. Tangkapan tradisi yang tidak berhubungan langsung dengan bencana juga diperlihatkan dalam tiga film, sehingga warna yang paling kental dalam film-film Palu adalah meletakkan film-filmnya dalam lingkaran budaya, entah itu memperkenalkan asal muasal, pengaruh, hingga dampaknya dalam kurun waktu belakangan: kebencanaan.
Vuya merupakan bentuk lintas disiplin antara film, seni tari, dan seni tekstil yang memiliki sejarah kepercayaannya. Hold and Kick menjelajahi budaya Mosivinti: sebuah tradisi melakukan tendangan ke betis. Turun ke Atas menceritakan Kembali kejadian bencana dan ingatan masa lalu dari titik likuifaksi paling terdampak dari mata seorang penyintas lansia. Karakter berpindah ke anak sekolah dalam film Pada Suatu Hari di mana mitigasi bencana diceritakan dari perspektif kearifan lokal. Ceritanya ada dua anak sekolah yang meninggalkan rombongan di area likuifaksi, tapi justru mendapatkan cerita dari warga setempat. Film ini memasukkan pengetahuan sejarah tentang bencana dan disampaikan dalam situasi Bersama anak-anak guna memahami lingkungan mereka. Informasi yang diwariskan turun-temurun juga hadir dalam Timbul Tenggelam. Bertempat di tempat penyintas Desa Tompe yang dilanda banjir rob, kisah bencana diturunkan melalui diskusi seorang kakek dengan cucunya. Penggambaran terhadap kelompok rentan juga dihadirkan lewat Yang Hilang dan Yang Tumbuh, di mana berkisar setahun setelah situasi bencana terdapat seorang siswi yang tidak menyelesaikan pendidikannya karena harus menikah setelah hamil. Terakhir adalah Saya Di Sini, Kau Di Sana. Film yang mendapatkan Special Mention pada kompetisi film pendek Oberhausen ini mengarungi persinggungan manusia dengan buaya yang berbagi ruang di zona merah.
Film menelusuri jejak-jejak awal pertemuan ini. Semua film akan mengarungi kehidupan Palu yang memiliki pengalaman terhadap budaya dan bencana, sekaligus eksplorasi bagaimana perspektif bencana dan kehidupan berlangsung di sana.
Karya-karya pilihan kota
Palu
© 2023 Apresiasi Film Indonesia. All Rights Reserved. Bekerjasama dengan Cinema Poetica dan Rangkai.